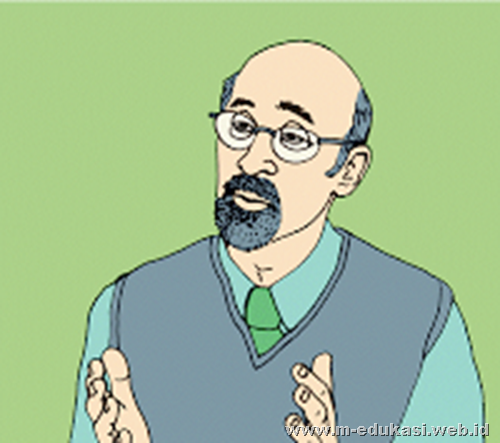Sekolah dasar merupakan salah satu organisasi pendidikan yang utama dalam jenjang pendidikan dasar. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 telah disebutkan bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.
Berdasarkan rumusan tersebut, dapat digarisbawahi bahwa sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan dasar diharapkan bisa berfungsi sebagai: (1) peletak dasar perkembangan pribadi anak untuk menjadi warga negara yang baik, (2) peletak dasar kemampuan dasar anak, dan (3) penyelenggara pendidikan awal untuk persiapan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pendidikan menengah. Kemampuan dasar utama yang diberikan kepada anak sekolah dasar adalah kemampuan dasar yang membuat bisa berpikir kritis dan imajinatif yang tercermin dalam modus kemampuan menulis, berhitung dan membaca. Ketiga aspek kemampuan dasar tersebut merupakan kemampuan utama yang dibutuhkan dalam abad informasi. 
Ditinjau dari komponennya, ada beberapa unsur atau elemen utama dalam organisasi sekolah dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) sumber daya manusia, yang mencakup kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, dan siswa, (2) sumber daya material, yang mencakup peralatan, bahan, dana, dan sarana prasarana lainnya, (3) atribut organisasi, yang mencakup tujuan, ukuran, struktur tugas, jenjang jabatan, formalisasi, dan peraturan organisasi, (4) iklim internal organisasi, yakni situasi organisasi yang dirasakan personel dalam proses interaksi, dan (5) lingkungan organisasi sekolah.
Ditinjau dari karakteristiknya, sekolah dasar merupakan suatu sistem organisasi. Sebagai suatu sistem organisasi, sekolah dasar bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi struktur organisasi dan perilaku organisasi. Struktur organisasi mengacu pada framework organisasi, yaitu tata pembagian tugas dan hubungan baik secara vertikal, horizontal dan diagonal. Hal ini bisa mencakup spesifikasi jabatan, pembagian tugas, garis perintah, peraturan organisasi, serta hierarki kewenangan dan tanggung jawab. Perilaku organisasi mengacu pada aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi. Organisasi sekolah dipandang sebagai suatu sistem sosial, yang di dalamnya terjadi interaksi antar individu untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu atribut yang banyak berkaitan dengan interaksi perilaku individu dalam organisasi adalah budaya organisasi.
Budaya organisasi adalah ikatan sosial yang mengikat anggota suatu organisasi secara bersama dalam memberikan nilai-nilai, alat simbolis dan ide-ide sosial. Budaya organisasi sebagai suatu kerangka kognitif yang berisi sikap, nilai, norma, perilaku, dan harapan yang dimiliki anggota organisasi. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis, Getzel dan Guba mengemukakan bahwa perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh dua dimensi, yaitu dimensi institusi yang dikenal dengan istilah nomothetic dimension, dan dimensi individu yang dikenal dengan istilah idiographic dimension. Ditinjau dari sisi institusi, setiap anggota dituntut untuk bertindak sesuai dengan peranan dan harapan untuk mencapai tujuan organisasi. Ditinjau dari sudut individu, setiap anggota dituntut untuk bertindak sesuai dengan pribadi dan kebutuhannya, maupun norma-norma institusi.
Bila diterapkan dalam organisasi sekolah dasar, ada tiga komponen yang berkaitan dengan budaya organisasi sekolah dasar, yaitu: (1) institusi atau lembaga yang perannya dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi sekolah, (2) guru-guru sekolah dasar sebagai individu yang memiliki kepribadian dan kebutuhan, baik kebutuhan profesional maupun kebutuhan sosial, dan (3) interaksi dari kedua komponen tersebut. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu mengintegrasikan kedua komponen tersebut, yakni peranan, tuntutan dan harapan lembaga, dengan kepribadian, dan kebutuhan guru, agar bisa mencapai tujuan organisasi secara optimal.
Keberhasilan organisasi sekolah banyak ditentukan keberhasilan kepala sekolah dalam menjalankan peranan dan tugasnya. Peranan adalah seperangkat sikap dan perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan posisinya dalam organisasi. Peranan tidak hanya menunjukkan tugas dan hak, tapi juga mencerminkan tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi.
Ada banyak pandangan yang mengkaji tentang peranan kepala sekolah dasar. Tiga klasifikasi peranan kepala sekolah dasar, yaitu: (1) peranan yang berkaitan dengan hubungan personal, mencakup kepala sekolah sebagai figurehead atau simbol organisasi, leader atau pemimpin, dan liaison atau penghubung, (2) peranan yang berkaitan dengan informasi, mencakup kepala sekolah sebagai pemonitor, disseminator, dan spokesman yang menyebarkan informasi ke semua lingkungan organisasi, dan (3) peranan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, yang mencakup kepala sekolah sebagai entrepreneur, disturbance handler, penyedia segala sumber, dan negosiator.
Berikut adalah empat belas peranan kepala sekolah dasar, yaitu: (1) kepala sekolah sebagai business manager, (2) kepala sekolah sebagai pengelola kantor, (3) kepala sekolah sebagai administrator, (4) kepala sekolah sebagai pemimpin profesional, (5) kepala sekolah sebagai organisator, (6) kepala sekolah sebagai motivator atau penggerak staf, (7) kepala sekolah sebagai supervisor, (8) kepala sekolah sebagai konsultan kurikulum, (9) kepala sekolah sebagai pendidik, (10) kepala sekolah sebagai psikolog, (11) kepala sekolah sebagai penguasa sekolah, (12) kepala sekolah sebagai eksekutif yang baik, (13) kepala sekolah sebagai petugas hubungan sekolah dengan masyarakat, dan (14) kepala sekolah sebagai pemimpin masyarakat.
Dari keempat belas peranan tersebut, dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu kepala sekolah sebagai administrator pendidikan dan sebagai supervisor pendidikan. Business manager, pengelola kantor, penguasa sekolah, organisator, pemimpin profesional, eksekutif yang baik, penggerak staf, petugas hubungan sekolah masyarakat, dan pemimpin masyarakat termasuk tugas kepala sekolah sebagai administrator sekolah. Konsultan kurikulum, pendidik, psikolog dan supervisor merupakan tugas kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan di sekolah.
Tugas kepala sekolah menjadi dua, yaitu tugas dari sisi administrative process atau proses administrasi, dan tugas dari sisi task areas bidang garapan pendidikan. Tugas merencanakan, mengorganisir, meng-koordinir, melakukan komunikasi, mempengaruhi, dan mengadakan evaluasi merupakan komponen-komponen tugas proses. Program sekolah, siswa, personel, dana, fasilitas fisik, dan hubungan dengan masyarakat merupakan komponen bidang garapan kepala sekolah dasar.
Di sisi lain, sesuai dengan konsep dasar pengelolaan sekolah, enam bidang tugas kepala sekolah dasar, yaitu mengelola pengajaran dan kurikulum, mengelola siswa, mengelola personalia, mengelola fasilitas dan lingkungan sekolah, mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, serta organisasi dan struktur sekolah.
Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat digarisbawahi bahwa tugas-tugas kepala sekolah dasar dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu tugas-tugas di bidang administrasi dan tugas-tugas di bidang supervisi.
Tugas di bidang administrasi adalah tugas-tugas kepala sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan bidang garapan pendidikan di sekolah, yang meliputi pengelolaan pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana-prasarana, dan hubungan sekolah masyarakat. Dari keenam bidang tersebut, bisa diklasifikasi menjadi dua, yaitu mengelola komponen organisasi sekolah yang berupa manusia, dan komponen organisasi sekolah yang berupa benda.
Tugas di bidang supervisi adalah tugas-tugas kepala sekolah yang berkaitan dengan pembinaan guru untuk perbaikan pengajaran. Supervisi merupakan suatu usaha memberikan bantuan kepada guru untuk memperbaiki atau meningkatkan proses dan situasi belajar mengajar. Sasaran akhir dari kegiatan supervisi adalah meningkatkan hasil belajar siswa.
Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya banyak ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan merupakan faktor yang paling penting dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi sekolah. Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola kantor, mengelola sarana prasarana sekolah, membina guru, atau mengelola kegiatan sekolah lainnya banyak ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Apabila kepala sekolah mampu menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan anggota secara tepat, segala kegiatan yang ada dalam organisasi sekolah akan bisa terlaksana secara efektif. Sebaliknya, bila tidak bisa menggerakkan anggota secara efektif, tidak akan bisa mencapai tujuan secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, bagaimana peranan kepemimpinan dalam pengelolaan sekolah, maka perlu diuraikan tentang konsep dasar kepemimpinan kepala sekolah dasar.